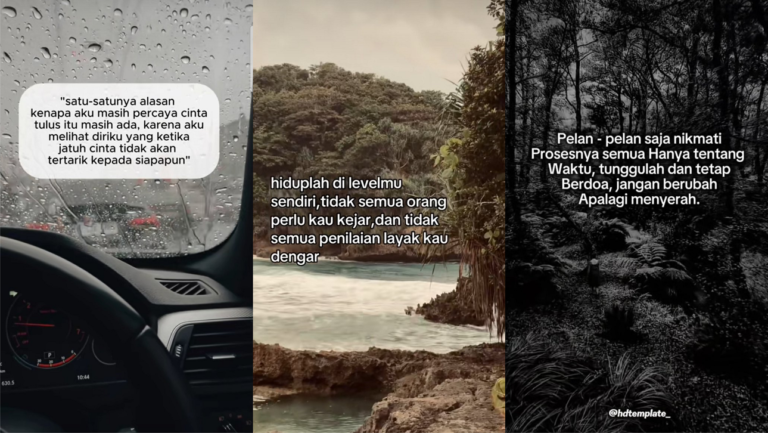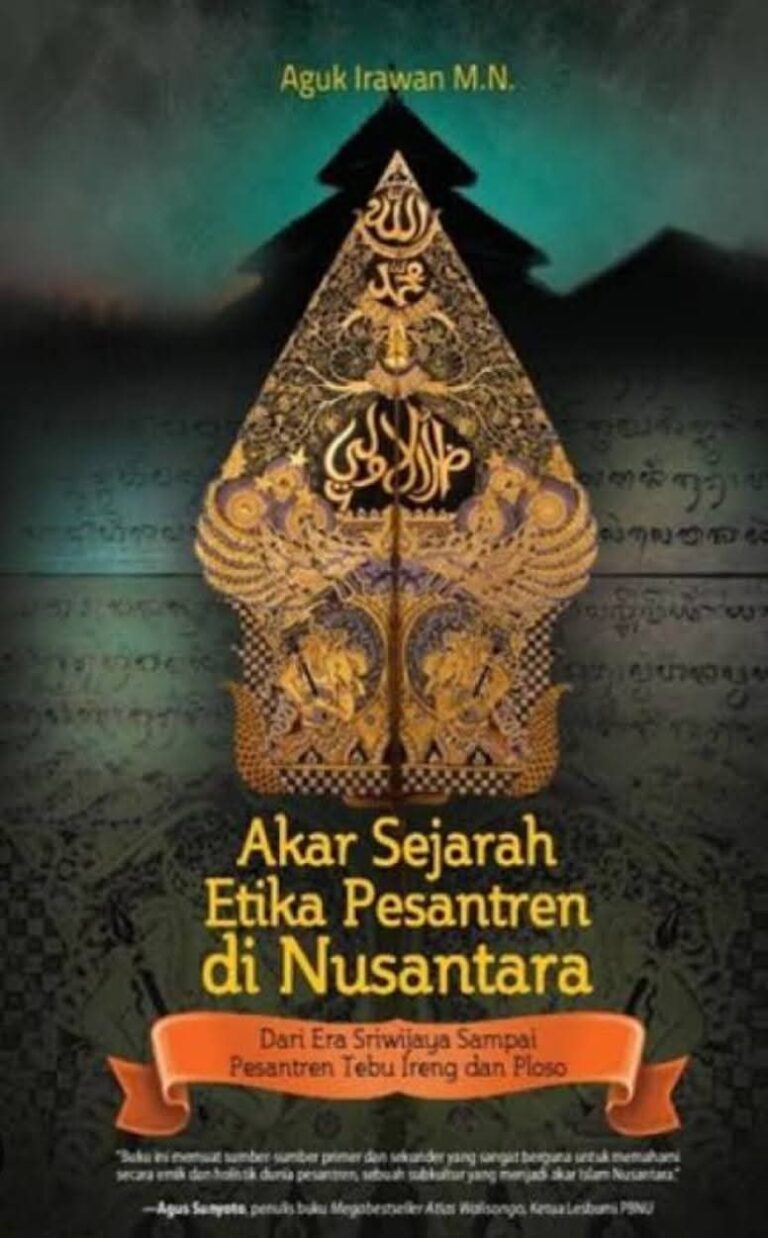Ada tokoh yang lahir dari rahim kekuasaan. Ada pula yang ditempa oleh perjalanan panjang lintas dunia—seni, intelektual, kebijakan, dan pengabdian sosial—hingga akhirnya berdiri di simpul sejarah yang menentukan.
Frederica Widyasari Dewi, yang lebih akrab dipanggil Kiki Widyasari, termasuk kategori yang kedua.
Ia bukan figur yang muncul tiba-tiba di ruang kekuasaan negara, melainkan hasil dari lintasan hidup yang panjang, berliku, dan sarat pembelajaran sosial.
Sejak remaja, Kiki telah mengenal ruang publik. Dunia seni peran memperkenalkannya pada disiplin, kerja keras, dan ketajaman membaca manusia.
Ketika ia tampil dalam sinetron kolosal Angling Dharma, memerankan permaisuri Raja Angling Dharma, publik menyaksikan sosok perempuan yang tidak sekadar menjadi ornamen kekuasaan, melainkan penopang moral dan kebijaksanaan.

Peran itu, disadari atau tidak, menjadi metafora awal perjalanan hidupnya: berada di sekitar kekuasaan, namun memilih jalan etika.
Tak banyak figur publik yang berani meninggalkan popularitas demi pendidikan. Kiki melakukannya.
Ia masuk ke Universitas Gadjah Mada, sebuah kampus yang sejak lama dikenal sebagai ladang persemaian intelektual kritis dan kesadaran sosial.
Di lingkungan ini, ia bersentuhan dengan tradisi diskusi, kepekaan terhadap problem rakyat, dan etos keilmuan yang menolak berpikir dangkal.
Fase kemahasiswaan ini—meski jarang disorot media—menjadi fondasi penting bagi cara berpikirnya tentang negara, ekonomi, dan keadilan sosial.
Pendidikan lanjutannya di Amerika Serikat mempertemukannya dengan wajah lain dunia: kapitalisme global yang efisien dan agresif, namun kerap dingin terhadap penderitaan sosial.
Ia mempelajari ekonomi modern dan pasar keuangan bukan sebagai dogma, melainkan sebagai sistem yang harus dipahami agar bisa dikoreksi.
Ketika kembali ke Indonesia, ia datang bukan sebagai penganut pasar bebas yang buta nilai, melainkan sebagai pembaca sistem yang sadar akan risikonya.
Karier profesionalnya di Bursa Efek Indonesia menjadi laboratorium nyata. Di sana ia menyaksikan langsung bagaimana modal bergerak, bagaimana keuntungan dibukukan, dan bagaimana kerugian sosial sering kali tidak tercatat.
Ia meniti karier dari posisi teknis hingga jajaran direksi. Pengalaman ini berlanjut di Kustodian Sentral Efek Indonesia dan kemudian sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas.
Ia memahami pasar modal Indonesia bukan dari laporan, melainkan dari praktik sehari-hari.
Justru dari jantung kapitalisme itulah kegelisahan etik tumbuh. Kiki melihat bahwa tanpa nilai, sistem keuangan akan selalu mengorbankan yang lemah.
Di republik dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi bukan sekadar persoalan angka, grafik, dan neraca. Ia adalah soal keberpihakan: siapa yang dilindungi, siapa yang diberdayakan, dan siapa yang terus tertinggal.
Dalam lanskap inilah ekonomi syariah seharusnya dipahami—bukan sekadar varian sistem keuangan, melainkan jalan etik untuk menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat.
Namun sejarah menunjukkan, potensi besar itu lama berjalan tertatih. Ekonomi syariah kerap dipinggirkan sebagai pelengkap, hadir dalam seminar dan jargon, tetapi belum sepenuhnya menjelma menjadi kekuatan struktural.
Maka ketika seorang teknokrat perempuan dengan rekam jejak panjang di pasar modal sekaligus penggerak ekonomi syariah tampil di panggung nasional, wajar jika umat Islam memberi perhatian serius.
Sejak pertengahan 2010-an, Kiki menempatkan energi intelektual dan organisasionalnya pada agenda yang kala itu belum populer: membangun ekonomi syariah sebagai ekosistem, bukan sekadar produk.
Dari titik inilah ia menemukan rumah pengabdian sejatinya di Masyarakat Ekonomi Syariah.
Sebagai Sekretaris Jenderal, lalu Ketua Pengurus Pusat, ia mengubah MES dari organisasi elitis menjadi simpul strategis umat—menghubungkan ulama dengan regulator, pesantren dengan pasar, dan ekonomi umat dengan kebijakan negara.
Di tangan Kiki, ekonomi syariah tidak lagi dibatasi pada perbankan, melainkan diperluas menjadi ekosistem halal yang menyentuh pangan, farmasi, fesyen, logistik, hingga pembiayaan UMKM.
Ia terlibat langsung menyatukan visi ulama dengan bahasa kebijakan negara melalui berbagai forum kolaborasi MES dengan Bank Indonesia, OJK, dan kementerian.
Industri halal ia dorong sebagai strategi nasional, bukan ceruk eksklusif. UMKM halal, pesantren, dan santri diposisikan sebagai aktor ekonomi, bukan sekadar objek bantuan.
Dalam berbagai forum MES, Kiki menegaskan bahwa ekonomi syariah harus berdiri di atas dua kaki: kepatuhan syariah dan daya saing global. Halal baginya bukan sekadar label religius, melainkan standar kualitas dan etika.
Dari sana ia mendorong penguatan rantai nilai halal, perluasan ekspor produk halal Indonesia, serta integrasi keuangan syariah dengan sektor riil—sebuah strategi yang dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga.
Ketika kemudian Kiki dipercaya menjadi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, khususnya membidangi perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen, agenda itu menemukan panggung struktural.
Dari posisi ini, ia berada di garis depan menghadapi wajah paling telanjang dari sistem keuangan yang tidak berkeadilan: pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan praktik keuangan yang menjerat masyarakat kecil.
Bagi umat Islam, persoalan ini bukan semata pelanggaran hukum, melainkan kezaliman ekonomi. Kiki memahami itu.
Karena itu, pendekatannya tidak berhenti pada penindakan, tetapi menekankan edukasi dan literasi keuangan—termasuk keuangan syariah—sebagai benteng awal agar umat tidak menjadi korban.
Ia mengaitkan literasi dengan etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai yang sejalan dengan maqashid syariah: menjaga harta, akal, dan martabat manusia.
Pengalamannya sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan memperkaya perspektif lintas sektor.
Ia memahami bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan keuangan harus berjalan seiring, serta bahwa negara tidak boleh netral ketika berhadapan dengan kejahatan keuangan yang menyasar rakyat kecil.
Di titik ini, pertanyaan tentang kepemimpinan OJK menjadi pertanyaan politik dan moral sekaligus. OJK bukan lembaga teknis semata, melainkan penentu arah.
Dengan kewenangan penyidikan yang dimilikinya, OJK dapat menjadi alat keadilan atau sekadar penjaga stabilitas semu.
Dalam konteks inilah, dukungan ulama dan umat Islam kepada Kiki Widyasari menjadi signifikan. Ia bukan hanya teknokrat perempuan, melainkan penggerak ekonomi syariah, jembatan antara ulama dan negara, serta pembaca sistem yang memahami bagaimana modal bekerja dan bagaimana ia harus dikendalikan.
Dukungan ini tentu bukan tanpa syarat. Ia adalah amanah.
Jika dipercaya memimpin OJK, Kiki memikul tanggung jawab besar: memastikan ekonomi syariah tidak menjadi kosmetik, industri halal tidak dikuasai segelintir modal, dan sistem keuangan tidak lagi menjadi alat pemiskinan struktural.
Sejarah sering bergerak pelan, melalui figur yang tidak berteriak, tetapi bekerja konsisten.
Dalam diri Kiki Widyasari, perjalanan hidup—dari panggung seni, ruang kampus, forum ulama, hingga pusat kebijakan negara—bertemu dalam satu garis besar: keberpihakan pada keadilan dan kemaslahatan.
Kini, umat Islam dan ulama dihadapkan pada pilihan sejarah: diam, atau memberi dukungan penuh pada arah baru ekonomi yang lebih halal, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Dukungan kepada Kiki Widyasari bukan soal personalitas, melainkan pilihan tentang masa depan ekonomi umat dan arah keadilan di negeri ini. ***